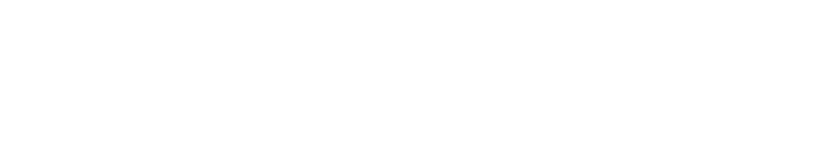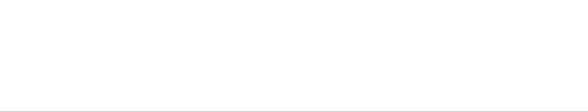Dialog interfaith dan intrafaith merupakan dialog yang harus intens dikembangkan pada setiap pemeluk kepercayaan. Keyakinan yang dianut oleh sebuah agama atau mazhab untuk mampu berjajal dengan realitas harus dikomunikasikan dan diekspresikan pada bursa ideologi. Karena ketika keyakinan atau kredo itu dipandang sebagai sebuah pilihan, setelah melakukan penelusuran dengan menggunakan piranti akal dan nurani, ia harus dipandang sebagai sebuah kebenaran yang menyediakan lahan bagi para pemeluknya untuk melesak meraih kesempurnaan insani dan kebahagiaan hakiki. Karena mencapai dan meraup kesempurnaan merupakan tuntutan fitrah manusia, apapun agamanya. Islam yang merupakan sebuah agama samawi semenjak kemunculannya menyambut dawuh dialog interfaith dan intrafaith ini. Islam yang diyakini oleh para pemeluknya tidak terkecuali harus turut dikomunikasi dan diekspresikan. Mengingat keyakinan kepada sesuatu berpotensi membahagiakan sekaligus menelantarkan. Namun bagaimana menemukan formula dan teraju untuk menjamin bahwa keyakinan tersebut merupakan sebuah keyakinan yang 100 % mengandung kebenaran dan tak lekang oleh panas serta tak lapuk oleh hujan. Artinya ia harus kokoh dengan argumen-argumen rasional dan filosofikal, dalam berjajal dengan agama-agama lainnya. Dalam hal ini, Islam menantang setiap agama-agama untuk menyodorkan argumen dengan nada “Qul Haatu Burhanakum inkuntum Shadiqin.” Sodorkan argumenmu sekiranya engkau merupakan orang yang benar.”
Demikian juga termasuk kepada pemeluk agama Islam sendiri, karena titah Ilahi ini bersifat umum, diseru kepada siapa saja karena keyakinan bukan warisan dari leluhur dimana hal ini sangat dicela oleh kitab suci agama Islam. Keyakinan harus Anda rengkuh sendiri dengan argumen sederhana sekalipun. Sebagaimana seorang renta pemintal benang ditanya oleh Nabi Agung Saw bagaimana engkau mengenal Tuhan, sang renta menjawab bahwa benang yang aku pintal ini menunjukkan aku sebagai pemintalnya dimana tidak mungkin ia ada dan tertata rapi tanpa aku yang mengadakan dan merapikannya apatah lagi semesta raya yang serba canggih ini tentu menunjukkan kepada sosok yang menciptakannya dan kita sebut sosok itu sebagai Tuhan Sang Pencipta.
Di samping ajakan untuk berdialog ini, Islam juga mengajarkan tata cara dan etika berdialog, dimana dawuh Ilahi menegaskan “Jadilhum billati Hiya Ahsan” Berdialog dan berdialektikalah kalian dengan mereka (siapapun) dengan cara yang lebih baik.
Pembaca yang budiman, kolom diberi judul Teologi Komparatif yang stressing lebih pada poin-poin ajaran penting dari setiap agama, ajaran dan isme dan perbandingannya dengan Islam atau mazhab pilihan. Perbandingan ini tentu saja meniscayakan telaah dan kajian dari obyek yang dikaji. Ke depan kami menjanjikan untuk sedapat mungkin melakukan studi komparatif antara agama, ajaran dan mazhab yang ada dan berkembang di dunia ini, misalnya Kristen, Yahudi, Budha, Hindu untuk agama. Dan isme-isme seperti Liberalisme, Humanisme, Sekularisme dan lain sebagainya. Lalu mazhab-mazhab popular teologi dalam Islam, seperti Asy’ariah, Mu’tazilah dan Imamiyah.
Pada kesempatan ini, kita akan melakukan komparasi antara teologi mazhab yang ada dalam Islam, dimana tiga pokok keyakinan yang menjadi obyek komparasi, Determinisme-Kebebasan Mutlak-In Between, Teori Kasb dan Tauhid dalam Penciptaan Asy’ariah, Mu’tazilah dalam sorotan teologi Imamiyah. Dimana dalam tulisan ringan ini, penulis juga berusaha menjelaskan (tabyin) dua pokok pemikiran Asy’ariah terkait dengan kebebasan manusia dan determinisme yang bertautan erat dengan masalah hukum kausalitas sekaligus melakukan perbandingan dua pokok pemikiran Asy’ariah secara global dengan mazhab Imamiyah. Tulisan ringan ini sengaja diturunkan buah dari “dialog intrafaith” dengan salah seorang pengguna budiman site ini namun di samping menjelaskan, karena pengguna yang dimaksud belum mengelaborasi dua pokok pemikiran yang dibelanya ini, dan menanggapi pandangan pengguna tersebut, tulisan ini juga bersifat impersonal artinya dialamatkan kepada siapa saja yang berselera mengetahui konsep-konsep pemikiran Asy’ariah, minimal ihwal konsep determinisme dan dua konsep yang dimaksud. Adapun ayat yang disebutkan pada tanggapan bag. Pertama tidak lebih dari sekedar menukil dan membacakan ayat bagi penulis yang kemudian tetap disebut sebagai klaim oleh penulis. Pembuktian yang dimaksud tidak disertai dengan argumen-argumen logis dan filosofis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti penukilan bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu, bahwa dengan izin Tuhan segala sesuatu berlaku, dan semisalnya tanpa mengelaborasi bahwa yang dimaksud pencipta dan penciptaan di sini apa? Dengan izin Tuhan segala sesuatu itu berlaku, maksudnya apa? Etc. Namun penulis berharap penanggap dapat menyediakan hal tersebut supaya melepaskan diri Anda dari tudingan klaim, menukil dan sekedar membacakan ayat sahaja. Ala Kulli Hall…
Masalah Kebebasan Mutlak, Determinisme dan In Between
Kalau tidak salah, beberapa postingan telah lewat ihwal Kebebasan dan Determinisme ini. Namun di sini dengan corak dan warna yang berbeda, kepada pembaca disuguhkan pandangan-pandangan Asy’ariyah dan Mu’tazilah yang digagas oleh para pembesar mereka dengan sandaran kitab-kitab induk teologinya, sekaligus kritikan dari Imamiyah.
Diriwayatkan bahwa Ghilan ad-Dimisyqi, yang berpendirian bahwa manusia memiliki ikhtiar (kebebasan memilih), berkata pada Rabi’ah ar-Ra’i, ilmuwan yang beraliran Jabariyah (determinisme): “Andakah yang menyatakan bahwa Allah menghendaki agar Ia dimaksiati?” Rabi’ah segera menjawab: “Andakah yang menyatakan bahwa Allah dimaksiati secara paksa?” Demikian juga pada suatu hari terjadi baku gea (dialektika), antara Abu Ishaq al-Farayini, pendukung aliran jabariyah (determinisme), yang duduk dalam majlis Shahib bin Abbad, dan al-Qadhi Abdul-Jabbar yang datang ke tempat itu, seorang tokoh Mu’tazilah yang mengingkari pengaruh takdir umum, berlawanan dengan pendapat Abu Ishaq. Ketika al-Qadhi melihat Abu Ishaq, segera ia berkata: “Subhana man Tanazzahu anil Fahsya (Mahasuci Allah yang terjauhkan dari perbuatan keji!” Ucapannya ini ditujukan sebagai sindiran kepada Abu Ishaq yang menisbahkan segala sesuatu kepada Allah, dan dengan demikian seakan-akan berpendapat bahwa Allah juga terkena sifat perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia). Mendengar itu, Abu Ishaq segera menukas: “Subhana man laa yajri fii mulkihi illa ma syaa.” (Mahasuci Dia yang tak suatupun berlangsung di dalam kerajaan-Nya kecuali yang dikehendaki-Nya!”) Jawaban ini menyindir al-Qadhi Abdul Jabbar bahwa seakan-akan ia menyatakan tentang adanya sekutu bagi Allah dalam wujud ini dengan membayangkan kemungkinan terjadinya sesuatu dalam wujud ini yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT, yakni perbuatan keji dan sebagainya.Apakah Tuhan menghendaki para hamba-Nya bermaksiat? Apakah para hamba lebih unggul dari Tuhan dan melakukan maksiat? Katakan kepadaku apakah jika Tuhan menahan hidayah dariku dan memutuskan aku terpuruk dalam jurang kebinasaan, apakah Dia melakukan kebaikan atau keburukan bagiku?[1]
Baku gea (dialektika) ini merupakan singgungan salah satu masalah yang terpenting dalam pembahasan teologi yang senantiasa menyita perhatian seluruh manusia khususnya kaum agamawan. Apakah manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam perbuatannya? Apakah kehendak dan kemauan manusia tidak dikalahkan oleh kehendak dan kemauan Tuhan? Apakah kehendak Tuhan termasuk seluruh perisitiwa dan perbuatan dan tiada satu pun dari peristiwa dan perbuatan ini keluar dari kehendak Tuhan?Apabila kehendak Tuhan bersifat umum, lantas bagaimana menjelaskan kebebasan manusia? Qadhi ‘Abdul Jabbar Mu’tazili meyakini kebebasan mutlak manusia dan memandang bahwa seluruh perbuatan mandiri dan bebas manusia berada di luar kekuasaan Tuhan. Sebagai kebalikannya, Abu Ishaq al-Farayini meyakini bahwa kehendak umum dan tanpa kecuali Tuhan, qadha dan qadar (dengan penafsiran deterministiknya) dengan redaksi “Subhana man laa yajri fii mulkihi illa ma syaa.” (Mahasuci Dia yang tak suatupun berlangsung di dalam kerajaan-Nya kecuali yang dikehendaki-Nya!”) merupakan sindiran yang ditujukan kepada Qadhi Abdul Jabbar yang beranggapan bahwa segala sesuatu berada di luar kekuasaan Tuhan. Dan tukasan dan isykalan Qadhi terhadap Abu Ishaq adalah bahwa apabila kehendak dan kemauan Tuhan kita pandang sebagai kehendak umum dan tiada satu pun perbuatan yang keluar dari ranah perbuatan Tuhan, dimana konsekuensi dari cara berkeyakinan seperti ini adalah keniscayaan penyandaran seluruh perbuatan buruk dan tercela kepada Tuhan.
Masalah determinasi dan kebebasan manusia semenjak dahulu kala merupakan masalah yang penting dalam bidang teologi. Determinisme adalah bahwa manusia dalam seluruh perbuatannya ia tidak memiliki kehendak dan kebebasan. Seluruh perbuatan manusia kesemuanyam terlaksana berkat kehendak dan kekuasaan Tuhan dimana kebebasan merupakan poin yang berseberangan secara interminis dengan pandangan ini. Seperti pada ayat “Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, “Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan nenek moyang kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang suatu apa pun.” Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Katakanlah, “Adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan (dan dalil untuk masalah ini)? Kemukakanlah Kami. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu hanyalah mengira-ngira.” (Qs. Al-An’am [6]:148) Dimana keyakinan deterministik tersebar di kalangan kaum Musyrikin yang menjadikan ayat ini sebagai pembenaran atas perbuatan-perbuatan tercela mereka. Dan juga patut disayangkan bahwa pemikiran semacam ini juga tersebar di kalangan kaum Muslimin dikarenakan beragam dalil di antara adalah alasan politis, sebagaiman yang disinggung pada postingan Mizan Keadilan Tuhan [3], sehingga menyebabkan mereka tercengkram paham jabariyah (deterministik). Ke depan pada postingan “Membincang Takdir Manusia” juga akan dijelaskan alasan yang dimaksud.
Determinisme Mutlak
Kini tiba saatnya menjelaskan paham jabariyah menurut kitab-kitab mereka. Pandangan determinisme mutlak ini disandarkan kepada Jahim bin Shafwan founding father firqah Jahimiyyah. Firqah ini adalah firqah yang pertama kali memperkenalkan ajaran determinisme mutlak. Menurut pandangan Jahimiyyah manusia sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan dalam perbuatannya ia terpaksa (majbur) dan hampa kebebasan dan kehendak. Seluruh perbuatan manusia sebagaimana pengaruh-pengaruh tumbuh-tumbuhan merupakan makhluk Tuhan dan manusia sama sekali tidak memiliki peran dalam mewujudkan pengaruh-pengaruh tersebut. Adapun penyandaran perbuatan itu kepada manusia merupakan penyandaran figuratif (majazi) bukan hakiki.[2]
Ucapan berikut ini adalah ucapan puak Jahimiyyah bahwa “Tiada satu pun perbuatan bagi setiap orang selain Allah dan perbuatan-perbuatan penyandarannya kepada makhluk hanya bersifat majazi.”[3]
Kasb (Perolehan)
Konsep determinisme mutlak tidak mendapatkan banyak pengikut. Banyak kelemahan dan borok dalam konsep ini dapat dijumpai dan pertentangannya dengan ayat-ayat lahir Qur’an. Sebagian berusaha, sembari bersikukuh dengan kekuasaan mutlak dan kehendak azali Tuhan, menjauh dari konsep determinisme mutlak ini. Sedemikian sehingga tetap ingin membuktikan pengaruh dan peran manusia dalam perbuatan dan pekerjaannya. Untuk menelurkan pandangan eskapis ini, teori perolehan (kasb) ini mengemuka. Mazhab teologi yang paling popular mengikuti, menyokong dan membela teori kasb ini adalah mazhab Asy’ariah, meski sebelum Asy’ariah tersebut mazhab Najjariyah (pengikut Husain bin Muhammad bin Abdullah an-Najjar(330 H) dan juga Dharuriyah (pengikut Dharar bin Amr) yang menyokong teori kasb ini.
Dasar teori ini adalah bahwa Tuhan merupakan pencipta segala perbuatan dan manusia hanya merupakan yang mewadahi dan memperoleah perbuatan-perbuatan tersebut. Dan mizan ketaatan dan maksiat juga bersandar kepada teori kasb (perolehan) ini, bukan penciptaan. Sejatinya, setiap perbuatan yang dilakukan manusia memiliki dua sisi:
1. Penciptaan yang bersumber dari Tuhan dan disandarkan kepada-Nya.
2. Perolehan (kasb) dari sisi manusia dan dinisbahkan kepadanya.
Dalam menjelaskan secara utuh teori perolehan atau wadah ini, terdapat banyak penafsiran dimana di sini kita akan menyebutkan sebagian dari penafsiran tersebut kemudian melakukan kajian kritis atas setiap penafsiran tersebut.
1. Asy’ari[4] menyatakan bahwa hakikat kasb adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kekuasaan hadis (yang dihasilkan) manusia yang merupakan pelaku dari perbuatan tersebut. Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa perolehan pengaruh kekuasaan (kekuatan) yang bersumber dari manusia dalam mewujudkan sebuah perbuatan.
2. Fadhil Qausyaji berkata bahwa “kasb adalah simultannya perbuatan manusia dengan kekuasaan dan kehendak manusia; artinya Tuhan secara bersamaan dan simultan dengan kekuasaan dan kekuatan manusia mengadakan sebuah perbuatan, tanpa adanya pengaruh atau interfensi kekuasaan manusia dalam mengadakan perbuatan tersebut.”[5]
3. Qadhi Baqilani (wafat 403 H) berkata: “Setiap perbuatan terdiri dari dua sisi: 1. Wujudnya perbuatan. 2. Julukan atau titel perbuatan yang merupakan turunan atas perbuatan tersebut dan kekuasaan manusia tidak memiliki kelayakan pengaruh pada wujud dan terolahnya perbuatan, melainkan hanya memiliki pengaruh pada julukan perbuatan. Atas alasan ini pengaruh pada julukan yang memiliki kelayakan untuk mendapatkan ganjaran atau hajaran. Sejatinya, wujudnya perbuatan makhluk Tuhan dan julukan perbuatan misalnya, julukan atau titel menunaikan shalat, berdusta, dan sebagainya merupakan perolehan manusia dan disandarkan kepada manusia. Baqilani dalam menjelaskan definisi yang diutarakan berkata: “Setiap orang orang menemukan perbedaan nyata di antara dua jumlah kalimat: A. mengadakan, kalimat seperti shalat (shalli), mengerjakan puasa (shama), dan berdiri (qama). Yang layak disandarkan kepada Tuhan kalimat-kalimat dan karakteristik bagian pertama dan julukan-julukan bagian kedua tidak patut disandarkan kepada Tuhan, melainkan disandarkan kepada manusia.”[6]
4. Taftazani menulis: “Kasb, penyandaran kekuasaan dan kehendak dari sisi manusia dan terciptanya perbuatan setelah itu dari sisi Tuhan, penciptaanya. Di sini maqdur (yang dikuasai) yang tunggal berada di bawah dua kekuasaan, akan tetapi dengan dua sisi yang berbeda. Dengan demikian, perbuatan dari sisi penciptaan yang dikuasai (maqdur) berasal dari Tuhan dan dari sisi wadah yang dikuasai berasal dari hamba (manusia).”[7]
Pada kesempatan ini, tentu tidak memungkinkan bagi kita untuk membahas dan mengkritisinya secara detil dan jeluk seluruh redaksi para pembesar Asy’ariah tentang teori wadah atau perolehan ini. Kita hanya akan menyinggung beberapa poin yang layak untuk dipertimbangkan.
Mengkaji Penafsiran Kasb
Masing-masing dari penafsiran kasb yang disampaikan di atas memiliki cela dan borok dimana di sini kita akan menyinggung sebagian darinya. Sebagaimana yang telah disinggung pada postingan Mizan Keadilan Tuhan [3], bahwa memahami teori kasb ini sama peliknya dengan memahami konsep trinitas dalam tradisi agama Kristen. Namun berdasarkan dari definisi yang disebutkan di atas mari kita lihat betapa rancunnya teori kasb ini.
Dalam mengkritisi penafsiran pertama, kita boleh bertanya apa peran kekuasaan yang dihasilkan manusia? Apabila penciptaan dan pengadaan perbuatan dalam artian yang sebenarnya kembali kepada Tuhan dan penyandaran kepada selain Tuhan adalah tidak benar, maka bagaimana kekuasaan yang dihasilkan manusia dapat berpengaruh? Apabila kekuasaan manusia memiliki pengaruh maka hal ini meniscayakan perbuatan itu juga merupakan ciptaan manusia. Dengan kata lain, apabila kekuasaan manusia disejajarkan secara vertical dengan kekuasaan Tuhan, maka ucapan puak-puak Asy’ariah meniscayakan bergabungnya dua kekuasaan atas sesuatu atau satu perbuatan (maqdur, yang dikuasai) dimana hal ini merupakan perkara yang absurd dan perbedaan sisi atau dimensinya tidak memiliki pengaruh dalam hal ini. Dan apabila dipandang kekuasaan manusia berada secara vertikal, top-down dengan kekuasaan Tuhan maka hal itu memestikan secara hakiki bahwa manusia juga memiliki kekuasaan dalam mengadakan sebuah perbuatan dan inilah konsep kebebasan (ikhtiar) dimana hal ini ditolak dan diingkari oleh puak-puak Asy’ariah.
Dalam mengkritisi penafsiran kedua dapat dikatakan bahwa, berdasarkan penafsiran ini, peran manusia hanya bersamaan dan simultan kehendak dan kekuasaanya dengan pengadaan perbuatan. Dan simultannya kehendak dan kekuasaan manusia dengan terwujudnya sebuah perbuatan yang merupakan makhluk Tuhan, tidak dapat menjadi pembenaran atas penyandaran perbuatan manusia, ganjaran (tsawab) dan hajaran (’iqab). Apabila puak-puak Asy’ariah menerima bahwa kehendak dan kekuasaan manusia dalam proses ini, kehendak dan kekuasaan sejatinya, maka dalam hal ini mereka harus mengakui bahwa manusia secara hakiki berada dalam silsilah sebab-sebab (‘ilal) terwujudnya perbuatan. Dan perbuatan tidak melulu merupakan makhluk Tuhan dan namun sayang seribu sayang, puak Asy’ariah tidak menerima keniscayaan ini. Namun apabila kehendak dan kekuasaan manusia ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang real oleh puak Asy’ariah, maka mereka harus menerima figuratifnya kehendak dan kekuasaan manusia dan memandang ada dan tiadanya kehendak dan perbuatan manusia itu harus dipandang sama dan sebagai konsekuensinya bermuara pada determinisme mutlak.
Kini mari kita beralih ke penafsiran ketiga. Isykalan yang patut diacungkan kepada Qadhi Baqilani dan orang-orang yang sepaham dengannya adalah apabila titel-titel yang mengikut pada perbuatan-perbuatan haruslah perkara eksistensial, dalam hal ini (berdasarkan pandangan Asy’ariah dalam masalah tauhid dalam penciptaan) titel-titel ini merupakan makhluk-makhluk Tuhan dan manusia secara asasi tidak memiliki peran dalam terwujudnya sebuah perbuatan, namun apabila titel-titel ini merupakan perkara-perkara mental (dzihni), yang memang demikian adanya, maka teori kasb ini juga akan kosong dari segala realitas dan semata-mata merupakan perkara wahmi (delusif) dan non-real yang dikembangkan dan disebarkan oleh puak-puak Asy’ariah.
Adapun kritik atas penafsiran keempat juga seperti isykalan-isykalan di atas. Sejatinya menyandarkan kehendak dan kekuasaan, dalam pengadaan perbuatan pengaruh dan interfensi real atau tidak real meniscayakan sesuatu yang telah dijelaskan pada kritikan atas penafsiran pertama dan kedua, juga dapat diacungkan kepada penafsiran keempat ini.
Dengan memperhatikan poin-poin di atas akan menjadi jelas bahwa pertentangan teori kasb dengan akal sehat atau tidak kompatibelnya teori kasb dengan akal sehat. Masalah ini terkadang secara selintasan diakui oleh pembesar Asy’ariah; misalnya Taftazani dengan redaksi di bawah ini mengakui kekurangan dalam menjelaskan dan memahamkan teori kasb ini. Ia berkata “Makna yang kami berikan atas teori kasb (di atas) sekedar yang penting saja, kendati kami tidak mampu meringkas redaksi dari hakikat bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang memiliki kekuasaan, kehendak dan kebebasan yang ia miliki merupakan makhluk Tuhan.”[8]
Pelbagai isykalan yang tergeletak pada teori kasb ini telah menyebabkan sebagian ulama besar Asy’ariah mengingkari dan menafikan teori ini; misalnya Imam al-Haramain Abu al-Mu’ali Juwaini yang menegaskan adanya pengaruh real kekuasaan manusia dalam perbuatan dan keberadaan selaksa kausalitas di alam semesta, sebagaimana Imamiyah. Dan menafikan kekuasaan dan peran mandiri manusia dalam perbuatannya adalah bertentangan dengan akal sehat dan perasaan.[9] Syaikh Sya’rani (w 973) juga senada dengan Juwaini menerima pandangan ini.[10] Demikian juga, tokoh seperti Muhammad Abduh (w 1323) yang menolak teori kasb ini dan mengakui pengaruh, peran dan kekuasaan real manusia dalam penciptaan perbuatan. Ahmad Amin memandang teori kasb ini sebagai istilah dan bentuk baru dari determinisme (mutlak).[11]
Tafwidh
Mu’tazilah bertolak belakang sine qua non dengan Asy’ariah yang memilih konsep tafwidh (pendelegasian). Berdasarkan pandangan ini Tuhan menciptakan manusia dan menganugerahkan kekuasaan dan kebebasan untuk mengerjakan segala perbuatan. Tuhan dalam hal ini telah mendelegasikan (tafwidh) kekuasaan dan kebebasan kepada manusia. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan keberpengaruhan didelegasikan kepadanya dan dengan demikian, Tuhan tidak memiliki peran pengaruh sama sekali dalam hukum kausalitas.[12]
Berdasarkan pandangan ini seluruh manusia dalam mengerjakan perbuatannya merdeka dan manusia sebagai satu-satunya sebab dari seluruh perbuatannya. Konsekuensinya adalah Tuhan sama sekali tidak ada campur tangan dalam pengadaan perbuatan manusia.Tuhan menghendaki bahwa seluruh manusia beriman kepada kebebasan yang dimilikinya. Demikian juga memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menjauh dari perbuatan buruk. Manusia juga dengan kebebasan yang ia miliki mengerjakan perbuatan baik dan menjauh dari perbuatan buruk. Dengan penjelasan ini pertama Tuhan terbebas dari perbuatan-perbuatan buruk; kedua, fungsi taklif, janji dan ancaman, ganjaran dan hajaran manusia tetap terpelihara.
Mu’tazilah dalam membela pemikiran dan keyakinannya mengemukakan pelbagai argumen rasional (aqli) dan referensial (naqli). Sebagaimana Jurjani menulis, argumen rasional Mu’tazilah berpijak pada landasan bahwa apabila manusia dalam mengerjakan seluruh perbuatannya tidak merdeka dan bebas, maka taklif akan rontok dan gugur. Demikian juga mengajarkan adab kepada manusia yang menjadi tujuan penciptannya akan runtuh; karena manusia apabila ia tidak merdeka dan bebas, secara asasi perbuatannya tidak akan dapat disandarkan kepadanya. Dan pengutusan para nabi akan sia-sia. Karena asumsinya adalah manusia bukan pelaku atas setiap perbuatannya dan dengan demikian ia tidak layak untuk mendapatkan ganjaran dan hajaran. Demikian juga penyandaran seluruh perbuatan buruk kepada Tuhan.
Mu’tazilah, di samping argumen rasional, juga berpijak pada dalil-dalil referensial (naqli) misalnya, “ Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri..” (Qs. Al-Baqarah [2]:79), “ Dan katakanlah, “Beramallah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amalmu itu..” (Qs. At-Taubah [9]:105), “ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Qs. Ar-Ra’ad [13]:11)
Argumen-argumen rasional dan referensial Mu’tazilah mendapatkan kritikan tajam dari puak teolog Asy’ariah.[13] Pada kesempatan lain kita akan membahas ayat-ayat yang dijadikan sandaran referensial. Namun sandaran rasionalnya patut mendapatkan perhatian sebagaimana poin di bawah ini:
Keniscayaan keyakinan tafwidh adalah manusia berada pada tataran kepelakuan mutlak dan sama sekali tidak memiliki hajat kepada Tuhan dimana hal ini tidak selaras dengan tauhid perbuatan; karena menjadi penyebab pembuktian dualisme dan sesuai redaksi Mulla Shadra membuktikan mitra dan sekutu yang tak berbilang bagi Tuhan. Mulla Shadra berkata bahwa keyakinan tafwidh lebih buruk dari keyakinan bahwa berhala-berhala mampu memberikan syafaat.[14]
Manusia dan segala perbuatan, segala fenomena dan dimensi yang berasal darinya merupakan bagian dari mumkinul wujud, dan perkara mumkinul wujud untuk mewujudkan dirinya ia berhajat kepada wajibul wujud. Apabila seluruh perbuatan manusia (mumkinul wujud) – kendati melalui pelaku merdeka – tidak bersandar kepada Tuhan (wajibul wujud), sekali-kali perbuatan ini tidak akan pernah terwujud. Maka tiada jalan lain selain menyandarkan perbautan manusia kepada Tuhan (wajibul wujud). Penyandaran ini sebagaimana yang akan dijelaskan ke depan adalah penyandaran vertical dan tidak berujung kepada determinisme.
Penyandaran perbuatan buruk kepada Tuhan dapat terjadi apabila seluruh perbuatan buruk itu kita sandarkan kepada Tuhan tanpa media, akan tetapi dengan perantara manusia merdeka sekali-kali perbuatan buruk tersebut tidak dapat disandarkan kepada manusia. Pada hakikatnya, Tuhan menghendaki manusia melakukan perbuatan baik sesuai dengan kebebasan yang ia miliki dan melarangnya untuk tidak melakukan perbuatan buruk sesuai dengan kebebasan yang ia miliki.
Kebebasan
Kini mari kita telisik pandangan yang tidak menafikan kebebasan juga tidak memutlakkan kebebasan. Dengan mengadopsi posisi in between ini tauhid perbuatan dan keadilan Ilah dapat tetap terjaga sekaligus kebebasan manusia serta menghindar dari keniscayaan invalidnya seperti invaliditas pengutusan para nabi, penetapan taklif (dalam pandangan Asy’ariah) dan syirik dan dualism (dalam pandangan Mu’tazilah).
Para teolog Imamiyah dengan inspirasi dari ajaran Ahlulbait As memilih konsep al-amr baina amrain. Sebuah konsep dimana untuk memahaminya secara jeluk harus dikuliti dalam sebagian pembahasan pelik filsafat, namun kandungan dari konsep tersebut dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbuatan-perbuatan manusia secara hakiki dapat dinisbatkan kepada manusia sekaligus kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan manusia dapat disandarkan kepada manusia karena berdasarkan kekuasaan dan kehendak perbuatan itu terjewantahkan. Dan sekaligus dapat disandarkan kepada Tuhan lantaran seluruh eksistensi dan pengaruh manusia – sebagai akibat Tuhan- bergantung kepada Tuhan dan bersumber darinya. Pada hakikatnya, manusia sebagai penyebab dan pelaku dari perbuatannya dalam hubungannya dengan perbuatan-perbuatannya, secara hakiki, namun tidak sejajar secara horizontal dengan kesebaban Tuhan, melainkan berdiri secara vertikal, top-down dan bergradasi. Untuk menjelaskan perbedaan pandangan tiga mazhab teologi terbesar dalam Islam ini, ada baiknya kita memperhatikan contoh yang baik yang diutarakan oleh salah seorang teolog dan juris Imamiyah, Ayatullah Khui Ra:
Anggaplah seseorang lantaran penyakit syaraf tangannya senantiasa bergetar sedemikian sehingga ia tidak memiliki kendali atas tangannya sendiri. Dan apabila sebilah pedang diletakkan di tangannya kapan saja pedang tersebut bisa jatuh dan melukai orang di sekitarnya. Kini apabila seseorang dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap realitas ini, diletakkan sebilah pedang di tangannya dan pedang tersebut terjatuh sehingga merebut nyawa seseorang lainnya, dalam kasus ini yang bertanggung jawab adalah orang tersebut karena pedang tersebut berada di tangannya, bukan pada orang yang tidak memiliki kontrol atas anggota badannya.
Sekarang perkara ini kita ilustrasikan pada seseorang yang sehat dan mampu mengendalikan seluruh anggota badannya. Apabila pedang ditaruh di tangannya dan ia juga terjerembab dalam perbuatan membunuh, pembunuhan ini disandarkan kepadanya bukan kepada orang yang diletakkan pedang di tangannya. Dan terakhir, anggaplah seseorang yang tangannya tidak bergetar, melainkan secara keseluruhan lumpuh dan tidak lagi bekerja secara aktif. Namun alat elektronik diberikan kepadanya dan ia dapat apabila alat tersebut menyala, maka ia dapat menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Anggaplah tombol untuk memfungsikan alat tersebut berada di tangan orang lain sedemikian sehingga sepanjang orang tersebut tidak menekan ON pada tombol tersebut, maka alat itu tidak akan beroperasi. Apabila seseorang yang memegang remote control mengoperasikan alat elektronik itu dan orang yang lumpuh seluruh anggota badanya melakukan perbuatan membunuh maka dalam hal ini perbuatan itu disandarkan kepada keduanya; lantaran ia sendiri memilih untuk menggunakan alat tersebut dan dengan kebebasan yang ia miliki ia melakukan tindakan pembunuhan ini. Dari sisi lain, disandarkan kepada orang yang memegang remote kontrol karena ia telah mengoperasikan seseorang yang lumpuh kekuataannya dan ia dapat kapan saja mematikan alat tersebut dan mencegah orang lumpuh itu dari perbuatannya.
Dengan memperhatikan tiga contoh kasus di atas menjadi jelas bahwa puak determinisme dan juga Asy’ariahyah – yang mengusung teologi determinisme – hubungan manusia dengan perbuatannya seperti contoh kasus pertama dan Mu’tazilah pada contoh kasus kedua. Adapun Imamiyah dapat ditinjau pada contoh kasus ketiga. Pandangan ini mungkin dapat dijelaskan dalam frame sistem filsafat Hikmah Muta’aliyah dengan tiga kaidah utama seperti berikut ini:
Wujud yang memiliki kehakikian (asil) bukan mahiyyat (kuiditas). Pada hakikatnya, yang diciptakan secara esensial dan hakiki adalah wujud. Dan tiada sesuatu yang lain kecuali pemahaman yang menjadi penjelas batasan-batasan seluruh wujud mumkin.
Wujud segala mumkinul wujud (seluruh makhluk di alam semesta) adalah ain rabt (murni hubungan) dan faqir mutlak; artinya seluruh makhluk tidak lain bersandar, bergantung dan berhubungan dengan wajibul wujud. Dan berangkat dari hal ini, ia tidak memiliki kemandirian dalam keberadaanya dan keberadaan seluruh makhluk itu tidak dapat digambarkan tanpa adanya ketergantungan kepada wajibul wujud.
Penciptaan atau pengadaan merupakan cabang dari wujud. Sebagaimana esensi dan keberadaan mumkinul wujud (seluruh makhluk) adalah ain rabt dan bergantung sepenuhnya kepada wajibul wujud, pengaruh dan perbuatan seluruh makhluk tersebut demikian adanya; karena sebuah fenomena sebagaimana ia maujud juga merupakan sumber pengaruh. Dengan demikian, apabila mereka mandiri dalam dzatnya, maka dalam kepelakuan juga akan memiliki kemandirian. Dan apabila pada dzatnya seluruh makhluk merupakan ain rabt (murni hubungan) dan bergantung, maka dalam kepelakuannya juga demikian adanya. Oleh karena itu, asumsi kemandirian sebuah fenomena dalam arsy perbuatan dan asumsi hubungan dan kebergantungannya pada tataran dzat merupakan dua asumsi yang kontradiktif dan tidak masuk akal.
Dari ketiga kaidah ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia disandarkan kepada manusia pada saat yang sama disandarkan kepada Tuhan; karena perbuatan-perbuatan manusia merupakan turunan dari keberadaanya dan tanpa syak bahwa keberadaannya di samping ia merupakan wujudnya sendiri, merupakan ain rabt dan bersandar kepada Tuhan.
Berdasarkan hal ini, manusia adalah ain rabt dan bergantung kepada Tuhan dan pada setiap detiknya memerlukan emanasi energi, kekuatan dan kehidupan darinya. Dengan demikian manusia pada detik ia mengerjakan sebuah perbuatan, dengan energi dan kehidupan ia melakukan perbuatan yang bersumber dari emanasi energi dan emanasi kehidupan dari Tuhan. Sejatinya perbuatan yang dilakukan manusia memiliki dua sandaran hakiki; Pertama, bersandar kepada manusia; karena bersumber dari dirinya sendiri dan berdasarkan kebebasan dan kekuasaan yang ia miliki; Kedua, bersandar kepada Tuhan; karena Tuhan pada setiap detiknya, bahkan detik ketika perbuatan itu dilakukan Dia menganugerahkan kehidupan dan kekuasaan kepada manusia. Dari sini perbuatan manusia merupakan perbuatannya sendiri pada saat yang sama juga merupakan perbuatan Tuhan. Berdasarkan pendekatan ini keberadaan manusia tidak lain kecuali hubungan mutlak kepada Tuhan.[15] Secara asasi di seantero semesta dari dimensi bahwa mereka bergantung dan berhubungan mutlak, mereka merupakan manifestasi kekuasaan dan kehendak, ilmu Tuhan dan inilah maksud al-amru baina amrain, manzilah baina manzilatain yang termaktub dalam riwayat.[16]
Tauhid dalam Penciptaan
Kendati masalah ini telah dibahas pada postingan sebelumnya, namun nampaknya kini pembahasan tersebut harus dikuliti lagi di sini sembari menyebutkan beberapa penafsiran dari tiga mazhab besar teologi dalam Islam.
Tauhid dalam penciptaan merupakan ajaran yang mendapat penegasan al-Qur’an dan Sunnah. Tauhid dalam penciptaan ini disepakati oleh seluruh firqah dan mazhab teologi dalam Islam; akan tetapi yang menjadi titik perbedaan, bagaimana menafsirkan dan menginferensi ajaran ini. Secara umum terdapat tiga penafsiran penting berkenaan dengan masalah ini. Penafsiran Asy’ariah, Mu’tazilah dan Imamiyah. Telaah global dari penafsiran ini menunjukkan bahwa penafsiran yang disuguhkan Asy’ariah merupakan penafsiran yang berbau deterministic. Dan penafsiran Mu’tazilah menyangsikan keumuman kekuasaan Ilahi dan tauhid dalam penciptaan.
Penafsiran Asy’ariah
Sebelumnya telah dikemukakan teori kasb yang diintrodusir oleh puak-puak Asy’ariah dalam membela dan mempertahankan “kemurnian” tauhid dalam penciptaan. Menurut Asy’ariah pengadaan dan penciptaan secara mutlak terbatas kepada Tuhan dan dalam tataran wujud, tiada satu pun yang berpengaruh dan berkreasi selain Tuhan. Segala sesuatu selain-Nya tidak memilik peran dan pengaruh dalam penciptaan dan pengadaannya baik secara mutlak atau secara ikutan. Asy’ariah berdasarkan pandangan ini telah mangkir dari hukum kausalitas dan proses pengaruh-mempengaruhi (ta’tsir dan ta’atstsur) seluruh maujud dan segala sesuatu di alam semesta. Menurut mereka pengaruh yang terlihat pada setiap fenomena adalah bersumber dari Tuhan. Misalnya membakar bukan merupakan pengaruh dan akibat dari api dan apabila dikatakan bahwa api itu membakar hal ini hanyalah merupakan kebiasaan Tuhan yang berlaku dimana dengan adanya api maka ia akan memunculkan panas dan membakar. Kalau bukan karena kebiasaan Tuhan maka tidak aka nada hubungan antara panas dan api. Dengan demikian dalam tataran eksistensi hanya terdapat satu yang berpengaruh dan satu sebab. Tuhan tidak menunjukkan kekuasaannya melalui pengadaan mekanisme kausalitas, namun Dia menjadi pengganti seluruh sebab dan musabab. Asy’ariah memandang perkara ini berlaku pada segala hal. Dan berdasarkan pandangan ini mereka mengambil kesimpulan bahwa seluruh perbuatan manusia juga, secara langsung merupakan perbuatan Tuhan dan manusia semata-mata memperoleh (kasb) atau menjadi wadah atas perbuatan ini. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas teori kasb ini meniscayakan tiadanya peran dan campur tangan hakiki manusia pada seluruh perbuatannya.
Padahal, mangkir dari hukum kausalitas dan peran pengaruh manusia dan fenomena semesta pada penciptaan pada beragam masalah bertolak belakang dengan nurani, akal sehat dan penemuan syuhudi manusia; Mengapa? Karena:
1. Dalam banyak perkara kita menemukan diri kita sebagai yang berpengaruh misalnya pelaku dan pengada segala konsepsi dan pemikiran mental (dzihni) kita adalah diri kita sendiri. Jelas bahwa bukti nurani merupakan sebaik-baik dalil dalam membuktikan hukum kausalitas.
2. Ketika seseorang yang tidak beriman kepada Tuhan hendak (iradah) menciptakan menara Monas dalam benaknya, ia dapat dengan mudah mengerangka sekaligus menghancurkannya dalam benaknya, mengusungnya dan menempatkannya di mana saja di belantara dunia dalam benaknya dimana hal ini menunjukkan peran mandiri pelaku orang tersebut dan wujud mental yang diciptakan tersebut eksis karena diwujudkan oleh pelaku tersebut dan hal ini membuktikan peran kekuasaan dan pengaruh pelaku manusia dalam penciptaan.
3. Menerima konsep kebebasan manusia dan hukum kausalitas, seperti klaim penanggap, namun mengingkari peran kepelakuan, penciptaan, pengaruh manusia dan setiap fenomena meniscayakan kontradiksi. Menerima kebebasan manusia dan hukum kausalitas meniscayakan peran kepelakuan, penciptaan, pengaruh manusia dan setiap fenomena.
4. Apabila hukum kausalitas dinafikan maka probabilitas untuk membuktikan wujud Tuhan menjadi tidak tersedia. Karena salah satu argumen dalam membuktikan wujud Tuhan adalah bersandar kepada hukum kausalitas. Karena Dialah Prima Causa (illatul ilal).
5. Penafian hukum kausalitas – atau menafikan peran kepelakuan manusia dan sepenuhnya menyandarkannnya kepada Tuhan meniscayakan gugurnya seluruh proposisi-proposisi turunnya wahyu, pengutusan para nabi, adanya ganjaran (tsawab) dan hajaran (iqab), karena semua perbuatan Tuhanlah yang melakukan.
6. Akal sehat tanpa teks-teks agama sekalipun turut menyokong hukum kausalitas. Maksudnya Anda Asy’ariahyyun tidak dapat meyakinkan kepada manusia yang tidak beragama dan tidak meyakini adanya Tuhan bahwa penyebab segala sesuatu itu adalah Tuhan, bersandarkan kepada kitab suci, bahwa Tuhan itu khaliq kullu syai, bagaimana Anda Asy’ariahyyun menjawab mereka yang tidak beriman kepada Tuhan, dengan al-Qur’an tentu meniscayakan circular reasoning (daur) dan tentu saja hal ini absurd. Namun dengan common sense, tanpa bersandar kepada teks-teks agama dapat membuktikan hal tersebut.
7. Teks-teks agama ternyata terbukti menyokong hukum kausalitas ini. Sejatinya tauhid dalam penciptaan merupakan ajaran yang bersumber dari agama. Berangkat dari sini, harus diperhatikan bahwa apa sebenarnya pandangan al-Qur’an dalam masalah ini? Apakah penafsiran Asy’ariah selaras dan senada dengan ayat-ayat al-Qur’an atau tidak? Apakah benar-benar al-Qur’an menafikan hukum kausalitas? Dengan memperhatikan dengan seksama ayat-ayat Qur’an maka akan menjadi jelas bahwa al-Qur’an mengakui secara resmi hukum kausalitas dan peran kepelakuan fenomena. Dan dalam banyak perkara hukum kausalitas disandarkan kepada perkara-perkara natural; misalnya pada ayat “Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menumbuhkan dengan hujan itu segala jenis buah-buahan sebagai rezeki untukmu. (Qs. Al-Baqarah [2]:22) Ba dalam redaksi bihi (dengan perantara) di sini bermakna penyebab; artinya sebab tumbuhnya segala jenis tumbuh-tumbuhan adalah air dan apabila tidak ada air maka tidak akan ada buah-buahan. Dan juga pada ayat “Dan di atas bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan (tapi berbeda-beda), dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama… “ (Qs. Ar-Ra’ad [13]:4) Redaksi “disirami dengan air yang sama” menujukkan peran penciptaan air dan pengaruhnya dalam tumbuh dan berkembangnya pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Di samping ayat-ayat yang telah disebutkan dengan beberapa pendahuluan filsafat dan logika, pada postingan Lagi tentang Determinisme dan Kebebasan Manusia, menegaskan penerimaan al-Qur’an terhadap hukum kausalitas. Dan tentu saja tidak akan menjadikan Anda musyrik sebagaimana keyakinan Asy’ariah yang telah dibuktikan absdurditasnya.
Penafsiran Mu’tazilah
Mu’tazliah berkebalikan dari Asy’ariah menerima hukum kausalitas dan pengaruh-mempengaruhi sebab di antara belantara akibat natural. Akan tetapi seluruh perbuatan mandiri manusia disandarkan hanya kepada manusia. Menurut mereka perbuatan-perbuatan manusia bukan merupakan makhluk Tuhan. Berdasarkan hal ini Mu’tazilah acapkali disebut sebagai “Mufawwidha”; karena mereka berkeyakinan bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mendelegasikan (tafwidh) kebebasan kepada manusia dalam perbuatannya. Penafsiran ini kendati memelihara peran kepelakuan sebab-sebab natural dan pelaku-pelaku insan, namun kritikan fundamental yang patut diacungkan kepada Mu’tazilah adalah mereka mengingkari tauhid dalam penciptaan; karena Tuhan tidak memiliki peran sama sekali dalam perbuatan-perbuatan mandiri manusia. Di samping itu, pensyariatan hukum-hukum, perintah dan larangan dari sisi Tuhan tidak lagi memiliki makna. Demikian juga pendelegasian (tafwidh) ini hanya dapat digambarkan ketika Tuhan tidak lagi dipandang sebagai penguasa mutlak dan kepenguasaan-Nya dinegasikan dari yang dikuasai-Nya (ma yamluk).
Nampaknya sumber kesalahan kedua penafsiran ini memandang kepelakuan dan pengaruh sebab-sebab dan pelaku-pelaku natural berada sejajar secara horizontal dengan kepelakuan Tuhan, padahal berdasarkan pada kaidah tepat akal konsepsi semacam ini adalah konsepsi salah kaprah. Sebagaimana yang akan disebutkan belakangan dengan penafsiran valid dan sahih, baik kepelakuan Tuhan dan juga kepelakuan sebab-sebab yang lain dapat tetap terjaga.
Penafsiran Imamiyah
Para teolog Imamiyah dengan ilham dan inspirasi dari ajaran para maksum As memandang bahwa penafsiran Asy’ariah ihwal tauhid penciptaan sebagai sikap ifrath dan Mu’tazilah sebagai tafrith (ekstrem). Imamiyah menawarkan konsep in between (laa jabr wa la tafwidh,,wal amru baina amrain). Menurut teolog Imamiyah dari tauhid penciptaan ini adalah bahwa tiada pencipta, pelaku mandiri mutlak dan secara esensial (dzati) selain Tuhan, dari sisi lain kepelakuan dan peran penciptaan pelaku-pelaku dan sebab-sebab natural dan manusia juga tidak dapat diingkari. Kepelakuan yang lain seperti pelaku-pelaku di antaranya manusia dalam hubungannya dengan perbuatan-perbuatannya, merupakan kepelakuan hakiki dimana pada saat yang sama berada secara vertikal, top-down, dengan kepelakuan Tuhan. Dengan memperhatikan ayat dan riwayat para maksum As tauhid dalam penciptaan ini dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini:
A. Sebagaiman yang telah lewat, dengan memperhatikan ayat-ayat Qur’an akan menjadi jelas bahwa dalam banyak perkara pengaruh yang disandarkan kepada sesuatu dan perkara-perkara natural; misalnya air yang menjadi penyebab tumbuh-berkembangnnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan madu sebagai penyembuh (syifa).
B. Al-Qur’an menisbatkan perbuatan-perbuatan kepada manusia dan memandang pelakunya adalah manusia dimana penyandaran secara langsung tanpa media (on the spot) kepada Tuhan adalah penisbatan salah kaprah, seperti berjalan, minum, tidur, menunaikan shalat, etc. Perbuatan-perbuatan semacam ini bertautan dengan manusia dan selainnya tiada pelaku lain.
C. Tuhan menitahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mentaati-Nya serta melarang manusia mengerjakan perbuatan buruk dan tercela. Masing-masing dari perbuatan baik ini diganjari dengan kenikmatan dan perbuatan buruk dihajar dengan azab. Nah, apabila manusia tidak memiliki peran dalam perbuatan-perbuatan baik dan buruk maka niscaya keseluruhan ganjaran dan hajaran ini tidak akan memiliki makna.
Sebagaimana tiga poin berikut ini di samping ayat seperti
قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ
“Katankanlah: “Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.” (Qs. Ar-Raad [13]:16)
Yang menjelaskan universalitas dan keumuman kepelakuan Tuhan pada segala sesuatu dan kita sampai pada kesimpulan bahwa sistem penciptaan dan segala jenis ciptaan yang eksis di dalamnya memiliki andil dalam mewujudkan peran pengaruhnya, akan tetapi peran pengaruh ini sesuai dengan izin dan taqdir Ilahi:
وَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ
“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.” (Qs. Shaffat [37]:96)
Dan
الَّذي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى
“Yang telah memberikan kepada makhluk-Nya segala sesuatu (yang mereka butuhkan), kemudian memberi petunjuk kepada mereka.” (Qs. Thaha [20]:50)
Dan
الَّذي قَدَّرَ فَهَدى
“Yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.” (Qs. A’la [87]:3)
Dan terakhir
وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللهَ رَمى
“Bukan kamu (hai Muhammad) yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.” (Qs. Al-Anfal [8]:17)
Sejatinya wujud segala sesuatu dan juga perbuatan, pengaruh, gerakan, diamnya bermuara pada qadha dan qadar Ilahi yang merupakan episode selanjutnya dari silsilah pembahasan di site ini. Tuhan menciptakan mekanisme eksistensi dan menjadikannya mengikut kepada hukum kausalitas dan faktor-faktor hakiki. Dengan demikian segala sesuatu berada secara vertikal, top-down dengan kehendak Tuhan memiliki peran penciptaan dan pengaruh pada perbuatan-perbuatan tersebut. So, proposisi “ada..tapi” tentu dengan pembuktian-pembuktian di atas tiada bermasalah dengan kemurnian Tauhid pada Penciptaan. Ajakan penanggap untuk tidak mengotak-atik masalah tauhid adalah ajakan yang tidak boleh diamini, karena dalam masalah tauhid sekalipun Asy’ariah sangat bermasalah. Jadi, saran penulis alih-alih Anda menghabiskan waktu untuk merekonstruksi teologi Imamiyah ihwal Tauhid dalam Penciptaan, yang sangat logis dan argumentatif, sebaiknya Anda menyelesaikan PR sendiri berupa borok dan cela teologi Asy’ariyah tentang Tuhan, Qur’an, Nabi, nasib manusia dan lain sebagainya. Nantikan saja bagaimana kami membuktikan kemusykilan Asy’ariah dalam masalah tauhid, pandangannya terhadap al-Qur’an dan nabi, qadha dan qadar. Tapi sebelum itu, penulis meminta kepada Anda atau siapa saja yang sepaham dengan Anda untuk menyuguhkan secara sistematis pokok-pokok ajaran Asy’ariyah yang bakalan menjamin terpeliharanya tradisi ilmiah dan dialog interaktif. Tentunya pihak redaksi akan senang hati memuat tulisan dan pembelaan Anda atas mazhab yang Anda yakini.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. Fathul Bari, al-Askalani, jil. 13, hal. 384, al-Qausyaji, Syarh Tajrid al-Aqa’id, hal. 340.
[2]. Syahristani, al-Milal wa an-Nihal, jil. 1, hal. 78, Abul Hasan al-Asy’ari, Maqalat al-Islamiyyin, jil. 1, hal. 312.
[3]. Al-Baghdadi, al-Firaq bain al-Firaq, hal. 194.
[4] . Al-Asy’ari, Abul Hasan, al-Lam’e fii ar-Rad ‘ala Ahli az-Zaigh wa al-Bida’, hal. 76.
[5] . Qausyaji, Syarh Tajrid al-‘Aqa’id, hal. 341.
[6] . Syahristani, al-Milal wa an-Nihal, jil. 1, hal. 97-98.
[7]. Syarh al-Aqa’id an-Nasafiyyah, hal. 117.
[8] . Syarh al-‘Aqâid an-Nasafiyah, hal. 117.
[9]. Syahristani, al-Milal wa an-Nihal, jil. 1, hal. 98-99.
[10]. Risâlah at-Tauhid, hal. 59-62.
[11]. Dhuhâ al-Islâm, jil. 3, hal. 57.
[12] . Lub al-Atsar fi al-Jabr wa al-Qadr, hal. 38.
[13]. Sa’ad ad-Din Taftazani, Syarh al-Maqasid, jil. 4, hal. 253-362.
[14] . Shadra al-Muta’allihin, al-Hikmah al-Muta’aliyah, jil. 6, hal. 370.
[15]. Ja’far Subhani, Jabr wa Ikhtiar, hal. 289-291.
[16]. Ruhullah Khomeini Ra, Thalab wa Iradah, hal. 74.